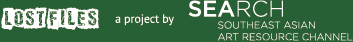
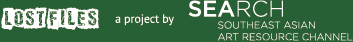

After Marina Abramovic © 2008. Oil on canvas. 200 X 200 cm
Agus Suwage: Still Crazy After All These Years
5 -31 July 2009
Jogja National Museum
9 October – 1 November
Selasar Sunaryo Artspace, Bandung
Dari luar, gedung Museum Nasional Jogja di Gampingan itu tampak sungguh tak istimewa. Selain selembar poster lebar tentang pameran tunggal Agus Suwage (Still Crazy After All These Years: 05 – 31 July 2009) yang membentang di dinding pojok depan, gedung itu seperti tak bergairah untuk menawarkan sesuatu yang layak kenang. Tapi setelah berada sekian menit di dalam, ruang-ruang gedung itu terasa memuai dan saya seakan melangkah perlahan di tempat lain yang kebetulan pernah saya datangi: Tate Modern Gallery dan Mori Art Museum.
Bangunan tua bekas kampus Institut Seni Indonesia (ISI) itu, dari segi fisik, tentu saja tak ada apa-apanya, bahkan mungkin memalukan, dibanding dengan gedung Tate yang terpacak di sisi Sungai Thames, London, atau museum Mori yang seakan mengambang di langit Tokyo, di lantai 53 Menara Mori di Roppongi Hills. Yang membuat gedung di Gampingan sore itu terasa mirip, kalau bukannya setara, galeri Tate dan museum Mori adalah benda-benda yang tersemat di dinding dan lantainya, dan tentu juga konstelasi benda-benda seni tersebut.
Kamar pertama yang saya masuki berisi karya yang memainkan cahaya dan bayang. Sepotong patung kepala dan torso babi digantung terbalik dari langit-langit ruang yang tampaknya dulu berfungsi juga sebagai teater tertutup. Dari katalog saya kemudian tahu bust babi hitam bertaring putih dengan telinga, mata dan moncong berona merah itu adalah bagian dari karya yang berjudul “Menjaga Malam” (2007). Judul itu bisa mengingatkan orang pada lukisan penting Rembrandt van Rijn yang berukuran sangat lebar yang juga memainkan cahaya dan bayang, “Night Watch.” Di sorot oleh dua lampu yang membentuk dua sosok di tembok, “Menjaga Malam” menghadirkan di ruang itu tiga kepala babi sekaligus, dan sesuatu yang lebih dari sekedar keanekaragaman sudut pandang dan pemaknaan.
Kamar kedua yang saya masuki diberi nama Kamar # 1: Genesis. Kamar ini menghimpun sekumpulan karya berukuran kecil dan sedang, yang dibuat di dekade 1980-an. Menurut katalog karya-karya ini menghadirkan dua unsur yang kelak terus ikut mengisi karya-karya Agus Suwage: ciri-ciri drawing dan unsur figuratif berupa sosok tubuh atau wajah manusia. Selain goresan drawing dan unsur figuratif, yang langsung membuat pandangan saya terenggut adalah cipratan merah, jingga dan warna hangat lain, yang muncul di sejumlah karya. Cipratan itu, yang seakan sisa dari kembang api yang melitas, terlihat juga di Kamar # 2: Room of Mine, yang diisi oleh karya berbentuk buku, yang konon sudah dibuat Suwage sejak awal kariernya.
Cipratan warna yang hangat itu, jejak dari hidup yang masih punya latu dan gelegak, membayang di benak saya ketika melangkah masuk kamar terakhir di lantai tiga — Kamar # 6: Tempus Fugit. Kamar ini tak diisi oleh warna apa pun kecuali hanya hitam dan putih. Beberapa lembar kertas pucat yang digambari garis gelap lugas dengan arang, terpasang di dinding tembok. Sebuah kerangka hitam berukuran besar tergeletak miring separuh melesap ke dalam lantai. Mungkin lantai itu ingin menelan kerangka itu. Mungkin kerangka itu yang ingin melenyapkan diri ke dalam lantai itu. Karya bagus di kamar terakhir itu, diberi judul yang seperti datang dari sebuah pergulatan diri yang panjang, Offering to an Ego (2007).

Offering to an Ego © 2007. Installation graphite. 60 X 350 X 150 cm
Di antara Genesis dan ruang terakhir Tempus Fugit — dua ruang yang seakan berdiri sebagai dua kutub yang saling kontras dalam hal pilihan warna, ukuran dan semangat karya — saya berjalan melewati sekian ruang yang setelah Room of Mine diurut dan kelompokkan menjadi The Years of Living Dangerously (kamar 3), Aku Melihat, Aku Mendengar, Aku Merasa (kamar 4), dan Beyond Autoscopy (kamar 5). Kamar nomor terakhir yakni 7: Still Crazy, dengan menarik diletakkan di tengah rangkaian.
Kata Crazy itu tampaknya dianggap sebagai pengertian inti yang perlu ditonjolkan dalam pameran retrospeksi ini. Selain menjadi bagian dari judul pameran (dipinjam dari salah satu komposisi Paul Simon), dan muncul di tajuk kamar nomer urut pamungkas, kata itu juga menjadi pengertian kunci yang disodorkan dalam diskusi yang diselenggarakan di tengah pameran (Still Talking Crazy). Jika crazy atau gila itu dipahami sebagai sesuatu yang bertaut rapat dengan yang ganjil, yang menjungkir balikkan nalar dan berada di luar pengetahuan publik, sesuatu yang tak terjangkau oleh awam atau sengaja dijauhkan karena kehadirannya bisa mengguncang tatanan pengetahuan dan kehidupan umum, maka yang bernar-benar gila itu tak langsung saya temui di pameran ini.
Memang ada sejumlah karya yang sungguh tak mudah dilupakan. Buat saya, Offering to an Ego; Ars Longa; Pause-RePlay; After Marina Abramovic; Pressure-Pleasure; Give Me More Question; Aku Melihat, Aku Mendengar, Aku Merasa; atau Holy Dog, misalnya, adalah sebagian deretan karya yang memang amat layak dikoleksi. (Sangat masuk akal jika sebagian besar karya ini tak dilepas oleh senimannya.) Tapi karya-karya seperti itu lebih menarik saya untuk tercenung, dan bukannya memaksa saya, untuk sekian bentar, menganga tercekam dengan otak yang hang karena dilabrak oleh sesuatu yang benar-benar sinting tak terduga.
Seni modern memang mewarisi semangat untuk tak menerima dunia apa adanya. Ia kritis dan bertekad untuk ikut mengubah dunia dan membebaskan segala kemungkinan-kemungkinannya. Jika melulu mengandalkan semangat yang terlalu berkobar, tanpa refleksi yang memadai, untuk terlibat melantangkan suara dan prasangka publik, karya bisa terjebak menjadi sekadar mewakili, sekedar menyalin hal-hal yang sudah sejak lama telah menjadi bagian dari wacana publik. Di sini karya menjadi sejenis parafrase dari apa yang telah menjadi bagian dari pengetahuan umum, dan bukannya pernyataan dari sesuatu yang benar-benar gila dan sebelumnya sama sekali tak terpikirkan.
Meski tak banyak, parafrase itu membayang juga di beberapa karya Suwage, dan terlihat misalkan pada instalasiAre You Going with Me (Perjalanan Tamat) — tentang kerakusan, ambisi dan kelatahan masyarakat modern. Parafrase visual itu memang tak mengatakan sesuatu yang sama sekali baru, tapi ia mengatakannya dengan cara yang memikat. Yang juga menarik adalah bahwa karya-karya itu tak terseret melemahkan diri dengan slomotan moral yang ketus dan simplistis. Jika ada yang terasa ketus pada karya Suwage, maka itu terhampar pada karya-karya yang titik pumpunnya adalah Suwage sendiri. Keketusan Suwage yang ditumpahkan pada dirinya itu terlihat jelas pada deretan karya yang berjejer di kamar Aku Melihat, Aku Mendengar, Aku Merasa. Ia berani, bahkan sengit, menyidik dan memblejeti dirinya, dan menghadirkannya lewat serangkaian potret diri.
Kesuntukan Suwage memblejeti diri itu mengingatkan saya pada beberapa artis. Rembrandt yang memang menunjukkan keunggulan kreatif antara lain pada lukisan potret diri adalah salah satunya. Pelukis yang langsung menonjol dan menyosok paling jelas di benak tentu saja adalah Frida Kahlo. Sosok perupa Mexico itu, dengan alisnya yang sulit hapus dari ingatan, muncul dalam sekian karya Suwage, menjadi semacam tribute, bahkan pengudusan.
Tapi jika potret diri karya Frida terutama menggali rasa sakitnya yang amat sangat justeru untuk menaklukkan bala yang ditimpakan oleh kekuatan luar terhadap tubuhnya, Suwage memblejeti pretensi-pretensinya dan mendulang sesuatu yang lebih berarti yang tertimbun dalam dirinya. Jika pada Kahlo potret diri menjadi semacam terapi dan ilham untuk menanggung hidup sembari menyelamatkan yang terbaik pada diri manusia, pada Suwage potret diri menjadi sebentuk meditasi dan pembersihan diri sembari mengingatkan potensi buruk pada manusia. Keduanya menggali diri demikian rupa, menjadikan tubuh sebagai pusat investigasi dan refleksi sambil menghadirkan sejumlah soal yang merundung manusia, dan dengan begitu menghapus batas epistemik atara tubuh dan dunia. Dalam hal Suwage, ia menghapus batas epistemik itu dengan lebih dahulu menghapus batas moral antara manusia dan binatang. Jika Kahlo tampak menggali lebih memumpun, Suwage jelas menggali lebih memencar.

Holy Dog © 1999 – 2000. Oil on canvas. Three panels. 72,5 X 72,5 cm
Penggalian Suwage yang memencar itu bisa berjalan jauh dengan berbagai kelokan dan percobaan yang membuatnya sampai pada wilayah kreatif yang menyatukannya bukan hanya dengan para maestro yang tinggal nama. Sejumlah karya mutakhir dia dengan jelas menautkannya dengan sekian perupa di berbagai belahan bumi yang masih sibuk merombak cakrawala seni rupa kontemporer dunia. Seperti semua bentuk kecerdasan yang tengah belajar, ada masanya memang di mana Suwage tampak mengapropriasi karya orang sembari melontarkan alegori, perpanjangan dari kecenderungan dia untuk tetap kritis. Tapi, pada karya di kamar Beyond Autoscopy dan Tempus Fugit, allegori dan appropriasi susut dan yang menonjol adalah tindakan yang mirip dengan apa yang oleh Mikhail Bakhtin disebut sebagai “vnenakhodimost.” Kata yang diterjemahkan jadi eksotopiitu kurang lebih berarti — dengan sangat menyederhanakan — upaya sang subyek yang sembari menyadari posisinya di luar, bergerak memahami dan “masuk” ke dalam karya yang dirujuk (Sang Lain), dan bekerja memperkaya sekaligus memperluas cakrawala karya itu. Ringkasnya, ketimbang mengambil dan meledek, Suwage menggunakan kekuatan yang ia punya untuk memberi dan merayakan.
Instalasi Pause-Replay terdiri dari 50 lembar drawing yang dibuat berdasarkan foto-foto yang merekam peristiwa penting dalam perkembangan seni rupa kontemporer. Teknik cat air yang membayang tipis yang digunakan Suwage seperti menciptakan atmosfir yang membuat masa silam bagai mendekat ke masa kini. Bayangan tipis itu hampir selalu ditemani oleh warna dasar yang lebih pekat, seperti biru dan terutama merah dengan berbagai gradasinya. Warna merah yang kadang menjelma jadi lidah api itu seperti berdenyar menyalurkan desir kalor ke sekitarnya. Tubuh-tubuh yang direkam dalam foto hitam putih buram itu seperti mencair dari kebekuan dan melayang ringan dari masa lalu yang padat peristiwa. Mereka yang suka gambar bermutu tapi tak begitu peduli pada sejarah seni rupa kontemporer — khususnya gerakan seni rupa feminis dan performance arts — tetap bisa menikmati instalasi ini. Mereka yang tahu sejarah, tentu akan mengalami sensasi lain menatap Pause-Replay menghidupkan lagi berbagai performance itu dengan segenap provokasi dan diskursusnya. Jika drawing Suwage memberi hidup baru pada tradisi gambar seperti yang disebut dalam katalog, maka eksotopi Suwage lewat teknik bayang — baik dengan cat air, tembakau maupun cat minyak — menyodorkan kekuatan baru pada foto-foto dokumentasi yang tak (belum) dipunyai oleh kamera.
Eksotopi Suwage terlihat lebih jelas lagi pada karya After Marina Abramovic yang “merujuk” The Hero, karya seniman kelahiran Serbia yang menyebut dirinya sebagai sang “grandmother of performance art.” Menurut Abramovic, The Hero — instalasi video yang dimainkan selama 17 menit — ia buat untuk mengenang keberanian dan ketabahan orang tuanya yang terlibat dalam revolusi, dan romans mereka yang dramatis di kancah revolusi itu. Memandang Abramovic duduk diam penuh percaya diri di punggung kuda jantan putih yang mungkin Andalusian mungkin Lippizaner selama 17 menit itu, tentu bisa terasa menjemukan, kendati rasa jemu (representasi segala bentuk ujian, fisik dan non fisik), dan perlawanan atas siksaan itu, adalah unsur sangat penting dalam karya. After Marina Abramovicmenyelamatkan kita dari keharusan menjalani 17 menit, tanpa harus kehilangan seluruh gagasan yang hendak disampaikan The Hero.
Kanvas Suwage itu seperti meringkas waktu — dengan hanya memandang sekilas After Marina Abramovic, kita bisa membayangkan sekaligus menghidupkan lagi The Hero. Di sisi lain, kanvas itu seperti merentang waktu, mengulur 17 menit itu menjadi tak terhingga. Dengan bendera yang tegak berkibar di atas kepalanya, Abramovic menunggu setia menanggungkan segala ujian sampai ia menjadi tengkorak. Selain maut, citra tengkorak jelas dekat dengan bayangan tentang waktu yang telah berlangsung sangat lama. Leleran cat yang jatuh mirip hujan mirip salju, dan angka-angka yang mungkin acak tapi ditata rapi seperti tanggalan di kalender, mengingatkan saya pada hari-hari yang rontok dan berlalu. Gabungan seluruh unsur visual ini, buat saya, menghadirkan di kanvas Suwage sejenis “kekinian yang kekal.”
Tentu saja The Hero tetap akan tegak tanpa After Marina Abramovic, sementara After Marina Abramovic akan menggema kian lantang dan panjang dengan The Herosebagai latar. Tapi yang jelas, Suwage berhasil masuk ke dalam The Hero dan lewat After Marina Abramovic ia menghadirkan bukan hanya kekuatan asal The Hero. Ia juga mencapai kualitas baru yang sebelumnya tak ada pada The Hero. Penanganan persepsi waktu yang cerdik lewat berbagai asosiasi visual itu hanyalah salah satu di antaranya. Penambahan kualitas baru sekaligus perayaan karya yang dirujuk itu membuat Suwage bergerak lebih maju dari Sherrie Levine pada karya, misalnya, After Walker Evans(1981) dan After Marcel Duchamp: A. P. (1991).
Selain permainan bayang dan waktu, terlihat juga permainan dan kecenderungan lain yang mendekatkan Suwage dengan dua perupa yang mungkin paling banyak dibicarakan di dunia saat ini: Jeff Koons dan Damien Hirst. Patung logam yang disepuh emas dan perak memang mudah mengingatkan kita pada Jeff Koons, perupa yang oleh Peter Scjehldahl di The New Yorker edisi 9 Juni 2008, disebut sebagai orang yang menghapus masa silam seni rupa dan mensketsa masa depannya. Dua buah karya Suwage bahkan diberi judul King & Queen Jeff Koons (2008). Tapi bukan karena logam yang disepuh kemilau, dan nama pada judul karya, yang merapatkan Suwage dengan Koons. Unsur yang mendekatkan itu adalah permainan ruang dan berbagai asosiasi yang melekat ke persepsi ruang itu yang kemudian dikoordinasikan untuk tujuan estetik.
Strategi kreatif yang menjadi karakter utama karya mutakhir Koons yang terkenal adalah pertautan dua kutub kontras yakni antara yang imut-imut, lucu, fun dan kemilau di satu kutub, dengan yang monumental dan menaklukkan ruang di kutub yang lain. Itulah yang terlihat pada patung topiari Puppy (1992) sejangkung 12,4 meter, atau Balloon Dog (1994–2000) setinggi 3 meter.
Suwage sudah bermain dengan persepsi dan asosiasi ruang berdimensi tiga sejak dekade 1990-an, misalnya pada karyaGive Me More Question (1997), Keberangkatan (1998), danPressure-Pleasure (1999). Beberapa tahun terakhir ia menggarap lagi persepsi dan asosiasi ruang ini yang membuahkan antara lain Untitled (2009) yang berbahan aluminium berukuran 2 meter, atau Offering to an Ego yang memerlukan satu kamar sendiri. Tapi jika Koons lebih banyak menggunakan volume besar untuk memainkan kontras dan menonjolkan lawan yang besar (yang fun dan imut-imut, misalnya), Suwage lebih sering menggunakannya untuk magnifikasi, untuk membesarkan yang memang besar. Menautkan Maut (tengkorak) dengan “obyek besar” — menghadirkan kematian lewat karya yang gigantis — pada karya Untitled (2009) misalnya, akan menghasilkan penyangatan dan bukan tegangan. Namun, di tengkorak besar aluminium itu, Suwage juga menatahkan, dengan agak samar, daun dan sulur yang merambat, citraan yang dekat asosiasinya dengan Hidup. Gambar daun dan sulur juga muncul menyudut di instalasi Offering to an Ego. Mungkin dua karya ini ingin menunjukkan, antara lain, bahwa sekalipun Maut tak terbatas, Hidup yang mungkin tak langsung tampak atau tersembunyi di pojok, selalu punya jalan untuk menjalarkan diri.
Ketika saya melihat dua karya itu sehari kemudian, saya membayangkan: apa yang terjadi jika Suwage menggunakan ruang besar untuk lebih menonjolkan yang kecil sepele, sembari mengubah pandangannya tentang maut, lalu bergerak lebih jauh dari, misalnya, Damien Hirst yang pada karya For the Love of God (2007) hendak menertawai Maut dan karena itu dihiasnya tengkoraknya secara keterlaluan dengan dilabur 8,601 berlian tulen. Menarik memang membayangkan karya-karya Suwage di masa depan yang mengolah ruang. Yang jelas, jika Koons kedodoran di karya berdimensi dua dan mumpuni di karya berdimensi tiga, seperti ditandaskan oleh Peter Scjehldahl, Suwage tampak bisa piawai di karya berdimensi dua dan tiga sekaligus. Setidaknya kemampuan Suwage menggarap karya berdimensi dua dan tiga tampak tak bertaut jauh.

Untitled © 2009. Aluminium. 200 X 125 X 143 cm
Di samping persepsi spasial dan asosiasi visual, ada permainan lain yang menautkan Suwage dengan salah satu praktek mutakhir seni rupa dunia. Permainan yang tak cuma berkisar di ranah cerapan indrawi ini berusaha melihat tembus dasar-dasar kebudayaan manusia yang tertutupi oleh kenyataan ekonomi dan politik, dasar-dasar yang paling membentuk hidup dan impian manusia. Kreasi artistik yang lahir ditandai oleh hadirnya aspek-aspek kehidupan dan kebudayaan pada sisinya yang paling vulgar dan profan, yang lalu dihadapkan dengan aspirasinya yang paling halus, paling tinggi. Tak jarang judul karya tampak tak punya hubungan sama sekali dengan “benda” yang disebut “karya.” Meski menjadi bagian sangat penting dari “karya,” judul di sini bukanlah “hamba”, bukan “wakil” — dan bahkan bisa menjadi “lawan” dalam sebuah oposisi biner — dari benda yang disebut “karya” itu. Pertautan dan tegangan antara benda dan judul itu membentuk kesatuan karya. Tegangan antara yang ada dan yang mungkin, antara yang benar-benar profan dan yang sungguh-sungguh sakral, dibentangkan seoptimal mungkin.
Damien Hirst membentangkan kontras itu dengan mengolah bangkai hewan yang mungkin menjijikkan, lalu memberinya selarik judul yang datang dari ranah kesadaran yang lain, ranah yang dekat dengan religi, kognisi dan puisi. Strategi penyematan judul seperti ini punya akar yang panjang dalam sejarah seni rupa. Kita tentu tak akan kesulitan menebak di ranah mana deretan tajuk Hirst berikut bertaut: The Holy Cow, The Sacred Heart of Jesus, Isolated Elements Swimming in the Same Direction for the Purposes of Understanding, Some Comfort Gained from the Acceptance of the Inherent Lies in Everything, dan The Physical Impossibility of Death in the Mind of Someone Living.
Saya merasakan tegangan dramatik, meski belum benar-benar optimal, dari kutub-kutub yang bertentangan itu pada karya Suwage yang menyatukan para pahlawan dan durjana, seperti pada karya Vox Mortis, Vox Orbis (2009), dan seriAku Ingin Hidup Seribu Tahun Lagi (2004-2008). Tegangan itu juga terasa pada sejumlah karya berdimensi dua yang melulur batas antara manusia dan binatang. Meski bermain di ranah yang lebih partikular, yakni hanya komunitas tertentu (tentara) paling luas hanya bangsa (Indonesia), instalasi Pleasure-Pressure agaknya adalah karya yang paling berhasil menghadirkan tegangan dan mengefektifkan hampir semua unsurnya.
Kecenderungan yang secara agak khusus mengkontraskan antara yang profan dan yang sakral, akan terasa makin jelas setelah melihat keseluruhan karya. Pameran ini memang sebuah karya tersendiri, dan pada “karya baru” inilah terbaca arus — yang sesekali naik ke permukaan — pemaduan kutub-kutub ekstrim itu. Sambil mengingat terobosan penting yang telah dibuat, saya pun menebak-nebak membayangkan: mungkinkah kecenderungan pengkontrasan itu bekerja habis-habisan, dan karya-karya yang akan datang bisa mencapai tegangan optimal antar kutub yang jangkauannya melintasi bangsa dan generasi? Ringkasnya: apa yang akan tercipta nanti jika Suwage tak cuma mencampur dan menjelajahi berbagai bahan, tak sekedar memainkan persepsi spasial dan asosiasi visual, tapi juga membaurkan dan membalikkan berbagai pandangan dunia?
Overview atas kostelasi karya dengan pengelompokan yang bersifat kronologis sekaligus tematis ini tak cuma memungkinkan munculnya dengan agak jelas tegangan antara kutub-kutub itu. Yang juga terlihat di sana adalah sejenis evolusi, dan pameran bagus ini jadi terbuka bagai sebuah novel bildungsroman dengan tokoh utama yang mungkin bernama Hidup, mungkin Kognisi, mungkin juga sesuatu yang belum punya nama yang kena. Mirip karya Suwage yang berujud buku — Room of Mine (1996) dan From Jungle to Civilization (1997) — pameran ini pun bisa dilihat seperti sebuah kitab di mana setiap kamar menjadi semacam bab. Perjalanan dari kamar ke kamar adalah perjalanan sang protagonis yang tumbuh dengan sekian percik daya hidup, berkembang dengan segenap gerak naik dan turun yang sibuk mengomentari dunia, lalu suntuk menginterogasi ego dan alter egonya, dan yang kemudian lega menerima keterbatasan manusia dan kekuasaan waktu. Di ruang akhir, saya seperti mendengar sayup-sayup antara lain puisi terakhir Chairil Anwar terbang menjauh, Derai-derai Cemara.
Tilas kembang warna yang muncul sejak di kamar 1 dan muncul terus di kamar-kamar berikutnya dengan berbagai perubahannya, memberi sensasi lain, dan saya merasa seperti berjalan dalam sebuah konser imaji. Konser itu dibuka dengan citraan cerah berlatar drawing yang kelam, disambung citraan logam dan bentangan kain yang setengah membubung, diimbuhi citraan vinyl dan benda-benda sintetis lain. Tak ketinggalan adalah bayang tipis berbagai warna yang tampak bergetar dengan denyar yang menjalar. Konser yang diisi ritme bentuk dan penjelajahan bahan ini, bergayut dengan sekian ikon dan penanda yang datang dari khazanah musik. Karena wataknya yang spasial, imaji-imaji visual terasa bersahutan dalam sebuah polifoni, sementara unsur naratif dalam karya membuat pameran ini jadi semacam heteroglossia. Jika dilihat secara temporal, konser ini tampak memainkan sebuah sonata. Ada introduksi yang muncul di kamar Genesis dan Room of Mine. Eksposisi hadir di kamar The Years of Living Dangerously dan Aku Melihat, Aku Mendengar, Aku Merasa. Pengembangan dan transisi menuju rekapitulasi tergelar di ruang Beyond Autoscopy.Tempus Fugit jelas jadi konklusi.
Di samping struktur linier sonata dan bildungsroman, yang juga sejajar dengan struktur argumen ilmiah-filosofis, bisa juga kita temukan struktur non linier — sejenis fraktal di mana fraksi (bagian), yakni karya individual, tampak mengandung keseluruhan; dan pola-pola tertentu senantiasa hadir berulang. Karya Suwage yang berujud buku dan dibuat belasan tahun yang silam itu seperti sudah mengandung seluruh pameran. Drawing, wajah dan figur, persandingan warna kelam yang tebal maupun tipis dengan bercak cerah dan berbagai nuansanya, jelas adalah unsur visual yang hadir nyaris berkala. Bahwa kamar nomor urut terakhir diletakkan justeru di tengah, dan bukan di ujung, rentetan kamar, buat saya, kian menegaskan struktur non-linier itu. Entah muncul secara intuitif atau memang lahir dari pemikiran yang benar-benar matang, peletakan kamar no 7 itu membuat struktur pameran ini secara visual mirip botol topologis Felix Klein.
Selain deretan karya yang sungguh beraneka ragam dan dikerjakan dalam kurun dua dekade lebih dari mungkin perupa terpenting Indonesia saat ini, penghargaan memang harus juga diberikan ke pelaksanaan pameran. Pameran istimewa ini menegaskan bahwa Jogja sungguh bisa menjadi kiblat senirupa dengan tarikan gravitasi yang melintasi batas-batas negara. Mereka yang bekerja mewujudkan pameran seni visual yang naratif dan musikal ini telah mengubah sepotong bangunan bekas menjadi sebuah tempat pameran yang isinya benar-benar tak kalah dari dunia luar.
~
Nirwan Ahmad Arsuka, born in South Sulawesi, writes on subjects spanning science, literature, art, history and philosophy. Most of his writings are published in KOMPAS, Indonesia’s most respected and most widely read newspaper, distributed throughout the archipelago.
Sorry, the comment form is closed at this time.
Aku suka ini. Terima kasih ARTERI.
Hahaha, Damien Hirst, eat your heart out!